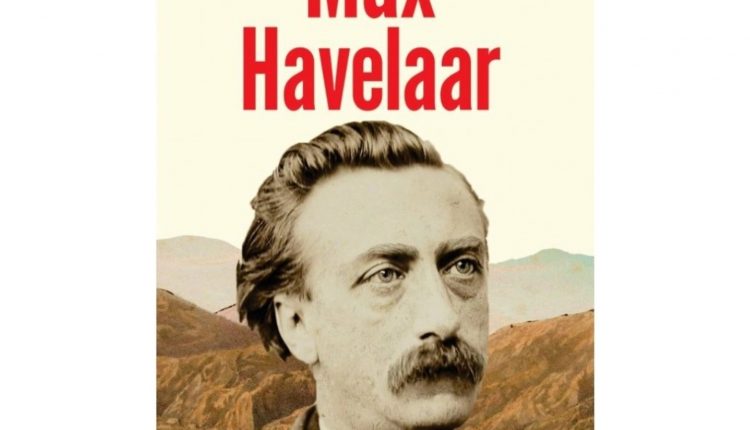Dapatkah Idealisme Individu Merombak Sistem?
Oleh: Naufal Febriyan
Penulis: Multatuli
Penerjemah: Wajib Danysalam
Penerbit: Anak Hebat Indonesia
Tahun terbit: 2024
Cetakan ke: Pertama
Jumlah halaman: 420
“’Kelaparan? Di Jawa, yang kaya dan subur, kelaparan?’ Ya, PEMBACA, beberapa tahun yang lalu, seluruh distrik dilanda kelaparan. Para ibu menjual anak-anak mereka untuk makanan, bahkan memakan anak-anak mereka sendiri,” begitulah salah satu kutipan dalam novel Max Havelaar, halaman 71. Menggambarkan kondisi Jawa yang kaya dan subur, tapi rakyatnya dilanda kelaparan akibat cengkraman kolonialisme.
Novel ini bercerita tentang perjuangan Max Havelaar, seorang Asisten Residen Lebak yang berusaha menegakkan keadilan, memberantas penindasan, perampasan, dan eksploitasi pribumi di Hindia Belanda. Novel ini berlatar waktu abad ke-19. Namun, upaya bijak Max–dalam rangka pengabdian pada pemerintah–justru tidak didukung, bahkan dikutuk oleh pemerintah itu sendiri. Aneh bukan? Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Idealisme pemimpin yang tertanam pada diri Max Havelaar ternyata hanya dimilikinya seorang diri. Max berakhir jatuh, tidak hanya jabatannya, harta serta tahta pun ikut jatuh bersamanya.
Cerita dalam novel ini sangat unik, Multatuli berhasil membuat alur cerita dari dua alur yang berbeda, dan memberikan latar yang kuat pada tokoh-tokoh cerita ini. Terutama pada tokoh utama, Max Havelaar. Tulisan tentang idealisme, hati nurani, serta sifatnya membuat pembaca merasa mengenal baik Asisten Residen yang hidup sekitar 200 tahun lalu itu.
Novel ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalaman pribadinya yang bekerja di bawah pemerintahan kolonial belanda. Ya, kejadian dalam novel ini sebagian besar berdasarkan kejadian nyata. Saya merasa terkejut ketika membaca dan kemudian mengetahui fakta bahwa pelaku utama penderitaan rakyat pribumi adalah bupati sekaligus pemimpin suku—yang mempunyai tanah kelahiran yang sama dengan orang-orang yang Ia rampas, perbudak, sekaligus mencambuknya. Diperkuat dengan bungkamnya pemangku jabatan pemerintahan kolonial yang ikut menikmati hasil keringat orang-orang jawa.
Banyak pengetahuan yang dapat dipelajari dalam novel ini selain dari pembahasan utamanya. Mulai dari Tata pemerintahan Hindia Belanda, idealisme kepemimpinan Max Havelaar, kondisi infrastruktur Hindia Belanda pada abad ke-19, pola kemunculan pemberontakan, pandangan orang belanda terhadap pribumi jawa—terutama pada sudut pandang agama—, dan lain-lain.
Meskipun demikian, ada hal yang perlu pembaca tahu sebelum hendak membaca buku ini. Cerita dalam buku ini melibatkan banyak tokoh, sehingga pembaca terkadang perlu membolak-balik halaman untuk mencari keterkaitan tokoh dengan konteks cerita yang sedang terjadi. Gaya bahasa yang digunakan sangat baku, pembaca yang terbiasa dengan format gaya bahasa novel kekinian mungkin akan “sedikit” kesulitan memahami beberapa kalimat. Tidak jarang, saya kembali ke awal paragraf untuk memahami konteks cerita.
Secara keseluruhan, buku ini sangat tajam dalam menyampaikan kritik pada pemerintahan kolonial belanda—menurut keterangan, pemerintah gelisah karena hadirnya novel ini. Ceritanya mampu membawa pembaca merasakan kesukaran yang dirasakan Max, maupun pribumi sekaligus. Novel ini sangat relevan untuk pembaca yang ingin mendalami sejarah Hindia Belanda yang tak tertulis di buku pelajaran pendidikan formal.
Max Havelaar adalah orang yang memiliki keinginan mengubah sistem—yang bobrok dan penuh penindasan—dengan idealisme nya yang adil. Tapi, pada akhirnya Ia justru dibungkam oleh sistem itu sendiri, ia kalah jumlah. Maka pertanyaannya, apakah kita masih yakin untuk mengubah sistem dengan cara yang serupa?[]
Redaktur: Nabil Haqqillah